'Roy Suryo Dipenjara Bukan Karena Meme, Tapi Karena Membongkar Ijazah Jokowi?'
Oleh: Damai Hari Lubis
Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
Jika publik melakukan kilas balik terhadap siapa saja yang pernah dilaporkan karena dianggap menista atau menghina individu, kelompok, atau golongan tertentu yang menimbulkan kebencian (hate speech) dan kemudian dapat dijerat dengan pasal penodaan agama berdasarkan KUHP jo. UU ITE, maka akan ditemukan sejumlah nama. Anehnya, banyak di antaranya justru tidak pernah sampai ke meja hijau.
Sebutlah nama-nama seperti Sukmawati, Ade Armando, Abu Janda (Permadi Arya), Denny Siregar, Yaqut, hingga Pendeta Gilbert.
Semua kasus mereka konon bisa “diselesaikan secara baik-baik”, entah melalui restorative justice, atau “fasilitas khusus” lain yang tak pernah transparan.
Namun mengapa perlakuan berbeda justru diterapkan pada Dr. Roy Suryo, mantan Menpora era SBY sekaligus pakar telematika dan IT, yang justru harus dipenjara terlebih dahulu sebelum divonis pengadilan?
Kasus yang menimpa Roy bermula dari repost meme sebuah stupa Buddha yang wajahnya diilustrasikan menyerupai Presiden Jokowi.
Padahal gambar tersebut adalah karya satir yang bersifat imajinatif, bukan replika yang secara pasti menunjuk pada wajah asli Jokowi.
Pertanyaannya, seberapa besar kesalahan Roy dibandingkan dengan pelaku-pelaku ujaran kebencian lain?
Mengapa terhadap Roy proses hukum dipaksakan hingga ke vonis penjara, sementara yang lain seakan dilindungi dan berakhir “damai”?
Lebih mencolok lagi, banyak konten serupa—bahkan lebih ekstrem—masih beredar di media sosial.
Gambar yang memperlihatkan Jokowi dalam peti mati ala Fir’aun, misalnya, justru tak pernah disentuh hukum.
Apakah karena yang menyebarkan bukan Roy Suryo, Rocky Gerung, Eggi Sudjana, atau HRS?
Apakah hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, atau dalam konteks hari ini: tajam ke oposisi, tumpul ke loyalis?
Menurut penulis, akar dari kriminalisasi Roy bukan semata karena meme stupa itu. Ada benang merah yang lebih dalam dan lama: analisis ilmiah Roy terkait kejanggalan ijazah Presiden Jokowi yang dipublikasikannya pada tahun 2020.
Ia mengungkap adanya keanehan pada font dalam ijazah Jokowi—yang menurut kajian Roy belum dikenal atau digunakan pada tahun 1985, saat Jokowi diklaim lulus dari Fakultas Kehutanan UGM.
Cuitan Roy tanggal 25 Februari 2020 pukul 13.27 WIB dari akun @KRMTRoySuryo2 yang memuat empat dokumen pendukung, termasuk cuplikan OPAC UGM dan skripsi serta ijazah Jokowi, menjadi bahan kritik yang tidak pernah dijawab secara akademik maupun institusional.
Tak ada klarifikasi, tak ada sanggahan berbasis ilmu. Yang ada justru serangan balik lewat jalur hukum dengan menjerat Roy melalui perkara meme stupa.
Inilah ironi. Sebuah kritik ilmiah dari seorang akademisi justru dibalas dengan pembungkaman.
Roy dihukum bukan karena meme-nya, melainkan karena menyentuh sisi gelap kekuasaan: keabsahan ijazah Jokowi.
Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh analisis Roy, mestinya menjawab dengan bukti akademik, bukan balas dendam lewat pasal karet.
Kasus Roy Suryo menjadi preseden buruk dalam demokrasi. Negara telah gagal membedakan antara kritik akademik dengan ujaran kebencian.
Bahkan, ketika seorang tokoh umat Buddha menyatakan tidak keberatan atas meme yang dipersoalkan, tetap saja Roy dijebloskan ke penjara.
Publik juga mencatat, akun pemula yang pertama kali mem-posting meme stupa itu—yang diduga bagian dari jaringan buzzer kekuasaan—justru aman dari jeratan hukum. Sementara Roy, yang hanya repost, diproses secara cepat dan keras.
Mengapa?
Karena Roy adalah simbol perlawanan intelektual terhadap kekuasaan yang anti-intelektualisme.
Ia adalah alumni UGM sejati—kampus yang dulu menjunjung tinggi ilmu dan moralitas, namun kini diduga sebagian aparaturnya telah terkontaminasi oleh kepentingan birokrasi dan kekuasaan.
Rektorat dan dekanat yang seharusnya menjaga marwah keilmuan, kini justru ditengarai terlibat dalam pembenaran ijazah palsu.
Bahkan seorang guru besar hukum pidana UGM dinilai turut menjadi bagian dari “advokat hitam” yang membela kejahatan intelektual dengan logika yang manipulatif.
Inilah wajah kelam dari extraordinary crime dalam dunia intelektual Indonesia: pemalsuan ijazah, konspirasi kekuasaan, dan pembungkaman ilmu pengetahuan.
Roy Suryo adalah contoh nyata bagaimana seorang intelektual bisa dikriminalisasi hanya karena mempertanyakan keabsahan sebuah dokumen akademik dari seorang kepala negara.
Bukan hanya Roy yang menjadi korban, tapi seluruh prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas ikut dilanggar.
Alih-alih mengapresiasi peran serta masyarakat dalam pengawasan kekuasaan, negara justru memenjarakan mereka yang bersuara.
Ini bukan sekadar pelanggaran hak Roy, tapi juga pelecehan terhadap ilmu pengetahuan.
Jika negara sungguh menjunjung rule of law, maka sudah seharusnya kebenaran dibuka secara jujur, dan analisis Roy diuji secara ilmiah, bukan dijadikan dasar untuk menutup ruang kebebasan akademik.
Dr. Roy Suryo mungkin telah menjalani 9 bulan penjara. Namun sejarah mencatat, bahwa ketidakadilan terhadapnya adalah simbol kegagalan negara dalam menghormati intelektualitas, ilmu pengetahuan, dan suara kebenaran.
Dan karenanya, selaku bagian dari civitas akademika sejati, Roy layak dikenang bukan sebagai pesakitan, tapi sebagai representasi heroik dari nalar waras yang kini makin terasing di negeri ini.
***



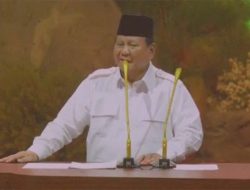







Artikel Terkait
Mengejutkan! Terungkap Data Jokowi di KPU: SD, SMP, SMA Kosong, Kok Bisa?
Minta Wartawan Keluar Saat Acara Danantara, Prabowo: Saya Banyak Menegur Direksi, Kan Gak Enak
Tuntutan Pergantian Wapres Harus Ditanggapi Serius Presiden, Komaruddin Watubun: Itu Purnawirawan yang Bukan Kelas Abal-abal
Viral Video Pelatih Futsal Banting Siswa SD di Surabaya, Korban Alami Cedera Berat